Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
XIV. Pertemuan dengan Gendis & Cakra

POV Gendis:
Sudah lima bulan lamanya Ganes sering menyebut nama pria itu—Wira. Awalnya, Gendis mengira itu hanya sekadar teman biasa, seseorang yang kebetulan hadir di kehidupan adiknya tanpa makna yang terlalu dalam. Tapi semakin hari, semakin sering nama itu muncul dalam percakapan mereka. Ada sesuatu di cara Ganes bercerita, nada suaranya yang sedikit lebih lembut, caranya menyebut nama pria itu dengan keakraban yang tak biasa.
Dan sejak saat itu, kegelisahan mulai mengisi pikiran Gendis.
Ia tahu betul bagaimana kehidupan Ganes setelah kehilangan Kavindra. Gendis adalah orang yang menyaksikan sendiri malam-malam penuh kelelahan dan air mata yang dipendam adiknya. Ganes berusaha tegar, membangun kembali hidupnya demi Amika, tetapi Gendis tahu betapa besar luka yang ditinggalkan. Dan kini, seorang pria baru muncul dalam hidupnya.
Gendis tidak bisa begitu saja merasa tenang.
Bagaimana jika pria itu tidak benar-benar serius? Bagaimana jika ia hanya ingin bermain-main? Bagaimana jika ia tidak bisa menerima keberadaan Amika? Ada terlalu banyak kemungkinan buruk yang berputar di kepala Gendis. Ia tidak ingin adiknya kembali terluka.
Malam itu, Gendis duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Tidur terasa sulit ketika pikirannya terus dipenuhi kekhawatiran. Besok adalah hari di mana ia akhirnya akan bertemu Wira untuk pertama kalinya—perkenalan resmi dalam makan siang di rumahnya. Ia ingin percaya bahwa Ganes berhak mendapatkan kebahagiaan, tetapi sebagai kakak, ia juga merasa bertanggung jawab untuk melindunginya.
Sebuah sentuhan lembut di pundaknya membuatnya tersentak. Cakra berdiri di samping ranjang, menatapnya dengan ekspresi penuh pengertian.
"Sayang..." suara suaminya terdengar lembut. "Kamu mikir apa, sih? Dari tadi aku panggil nggak denger."
Gendis mengangkat wajahnya, mencoba tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Mas. Cuma kepikiran persiapan buat besok."
Cakra menatapnya lebih lama sebelum akhirnya duduk di sampingnya. "Kamu khawatir sama Ganes?" tanyanya hati-hati.
Gendis menghela napas panjang, akhirnya mengakui kegelisahannya. "Aku takut, Mas," ucapnya lirih. "Ganes itu sudah cukup banyak melewati hal sulit. Aku nggak mau dia harus mengalami sakit hati lagi."
Cakra menggenggam tangan istrinya, jempolnya mengusap punggung tangan Gendis dengan lembut. "Gendis, Ganes sudah dewasa. Dia berhak memilih jalannya sendiri. Kita nggak bisa selalu melindunginya dari segalanya."
"Tapi kalau Wira bukan orang yang tepat?" Gendis masih ragu. "Kalau dia cuma sekadar mampir lalu pergi?"
Cakra tersenyum kecil. "Itu sebabnya kita akan lihat sendiri besok, kan? Kita nilai dia. Kalau dia benar-benar serius dan baik, kita dukung. Tapi kalau dia nggak cukup baik untuk Ganes, kamu tenang aja. Aku pasti ada di belakangmu buat jagain dia bareng-bareng."
Gendis menatap suaminya, kehangatan merayapi hatinya. Ia tahu, Cakra selalu punya cara untuk menenangkannya.
Malam ini, kegelisahan itu belum sepenuhnya hilang. Tapi setidaknya, Gendis merasa lebih siap menghadapi esok hari—siap memastikan bahwa tak ada lagi yang akan menyakiti adiknya.
...
Gendis berdiri di depan rumah bersama Cakra, lengannya terlipat di dada. Matanya terus menatap ke arah jalan, menunggu kedatangan Ganes dan pria itu—Wira.
"Relax sedikit, Dek," ujar Cakra sambil menyenggol lengannya pelan. "Kamu kelihatan kayak satpam perumahan."
Gendis mendelik tajam ke arah suaminya. "Kalau perlu, aku pasang portal sekalian, Mas."
Cakra hanya tertawa, sementara Gendis kembali fokus ke depan. Tidak butuh waktu lama sebelum sebuah mobil berhenti di depan pagar rumah mereka. Jantung Gendis berdebar lebih kencang—ini saatnya.
Wira turun lebih dulu. Gendis mengamatinya dengan seksama. Kemeja putih bersih, celana kain rapi, sepatu mengilap. Pria itu jelas berusaha tampil sebaik mungkin, dan Gendis bisa melihat usahanya. Tapi tetap saja, itu tidak cukup untuk langsung membuatnya percaya.
Saat itulah, tiba-tiba Cakra berseru, "Loh? Mas Wira?"
Wira tampak sama terkejutnya. "Loh? Pak Cakra?"
"Owalaahh..." Cakra langsung tertawa lebar. "Dek, ini Mas Wira yang dulu sekantor sama aku di Pertamina!" katanya sambil melirik ke arah Gendis dan Ganes.
Gendis dan Ganes saling pandang sebelum ikut tertawa kecil. Dunia memang sempit.
Gendis sedikit melonggarkan lengannya yang terlipat, tetapi tetap menjaga ekspresinya netral. "Jadi kalian dulu satu kantor?" tanyanya, mencoba memastikan.
"Iya, Mbak," jawab Wira sambil tersenyum, masih terlihat sedikit kaget. "Mas Cakra ini dulu senior saya di Pertamina. Saya banyak belajar dari beliau."
Cakra terkekeh, menepuk bahu Wira dengan santai. "Wira ini orangnya rajin, Dek. Dulu paling sering pulang terakhir dari kantor."
Gendis mengangkat alis, berpikir sejenak. Lalu, dengan nada datar, ia bertanya, "Pulang terakhir karena kerja keras atau karena main game di komputer kantor?"
Wira langsung tersedak udaranya sendiri, sementara Ganes memukul pelan lengannya. "Mbak!" protesnya setengah tertawa.
Cakra malah makin terbahak. "Hahaha! Dulu emang ada tuh yang suka main game, tapi Wira bukan salah satunya. Dia beneran rajin, Dek."
Gendis masih mengamati Wira, mencari tanda-tanda apakah pria itu benar-benar bisa dipercaya. Sementara itu, Amika tiba-tiba berlari kecil ke arah mereka dari dalam mobil, tangannya terulur ke Wira. "Wiwi!" serunya riang.
Gendis sempat menahan napas. Amika tidak pernah secepat itu akrab dengan orang asing. Wira tersenyum lebar, langsung membungkuk untuk menyambut gadis kecil itu. "Hai, Amika! Kamu udah makan siang belum?" tanyanya lembut.
Gendis masih berdiri tegak di tempatnya, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ia tidak akan langsung memberi restu, tentu saja. Tapi setidaknya, melihat cara Wira bersikap pada Amika membuat hatinya sedikit lebih tenang.
Sedikit.
Karena jika pria ini berani melukai adik dan keponakannya, Gendis pasti akan menjadi orang pertama yang membuatnya menyesal.
...
Makan siang berlangsung dalam suasana yang jauh lebih akrab daripada yang Gendis bayangkan. Cakra dan Wira terlibat dalam obrolan panjang tentang masa lalu mereka di kantor, mengenang rekan-rekan lama, pekerjaan yang penuh tantangan, dan kebiasaan-kebiasaan lucu yang mereka lakukan bersama. Gendis mendengarkan, sambil sesekali melirik ke arah Wira.
Dia berbicara dengan tenang dan sopan, tertawa ringan di tengah percakapan, tetapi yang paling mencuri perhatian Gendis adalah cara Wira melirik Ganes yang duduk di sampingnya. Bukan sekadar tatapan suka biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam—ketulusan yang tidak bisa disembunyikan.
Gendis merasa hatinya sedikit lebih tenang, meskipun dia tetap tidak bisa mengabaikan rasa khawatir yang mengendap di dalam dirinya.
Setelah makan, Ganes membawa Amika ke kamar mandi. Gendis memutuskan ini adalah saat yang tepat untuk berbicara. Dengan hati-hati, dia meletakkan sendoknya, lalu menatap Wira dengan tatapan serius.
"Kamu yakin bisa bersama Ganes?" tanyanya langsung.
Wira tidak terkejut dengan pertanyaan itu. Dia menegakkan punggungnya, menunjukkan ketegasan dalam diri, lalu menatap Gendis dengan mata yang tenang. "Iya, Mbak. Saya yakin saya siap bersama Ganes. Saya ingin mendukungnya, menemani dia."
Gendis menghela napas panjang, perasaan campur aduk di hatinya. "Kami sangat menyayangi Ganes dan Amika. Saya tidak akan membiarkan mereka disakiti lagi," ujarnya, suara lembut tapi penuh tekad.
Wira mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Saya mengerti, Mbak. Saya tidak ada niat mempermainkan Ganes. Saya sayang sama dia, dan juga Amika. Saya tahu saya bukan ayah kandungnya, tapi kalau saya diberi kesempatan, saya ingin menjadi bagian dari hidup mereka."
Gendis terdiam sejenak, matanya mengamati Wira dengan cermat. Kata-katanya terdengar tulus, namun hatinya masih ragu. Seumur hidupnya, Gendis selalu melindungi Ganes. Dia sudah cukup banyak melihat orang yang datang dan pergi dalam hidup adiknya, dan ia tidak ingin melihat adiknya terluka lagi.
Namun, meskipun keraguannya belum sepenuhnya hilang, ada sesuatu dalam diri Wira yang membuatnya berpikir dua kali. Tatapan Wira yang penuh harapan, keinginan untuk benar-benar menjadi bagian dari hidup Ganes dan Amika, membuatnya merasa ada kemungkinan baik dalam hubungan ini.
"Jika kamu serius," Gendis akhirnya berbicara dengan pelan, "pastikan kamu ada di sana untuk mereka, dalam suka dan duka. Ganes tidak mudah membuka hati, dan Ami—Ami... dia butuh seseorang yang benar-benar ada untuknya."
Wira mengangguk lagi, kali ini lebih lembut. "Saya mengerti, Mbak. Saya tidak akan mengecewakan mereka."
Gendis merasakan ketulusan dalam kata-kata Wira, tetapi tetap saja, ia ingin lebih banyak waktu untuk melihat sejauh mana komitmen pria ini. Namun, untuk saat ini, ia merasa sedikit lebih tenang.
Dan mungkin—hanya mungkin—Wira bisa menjadi bagian dari kehidupan adiknya yang lebih baik. Tapi satu hal yang pasti, Gendis akan tetap menjaga mereka, tak peduli apapun yang terjadi.
...
Setelah makan siang yang hangat, suasana rumah Gendis mulai terasa lebih santai. Gendis dan Ganes ada di dalam untuk membereskan meja makan, namun Wira dan Cakra memilih untuk melangkah ke teras, mencari udara segar dan sedikit ruang untuk berbicara berdua.
Mereka duduk di kursi panjang, Wira menyalakan sebatang rokok dan Cakra mengikuti dengan rokoknya sendiri. Asap tipis melayang di udara, bercampur dengan angin sore yang tenang. Hanya ada suara detak jam dan gemerisik daun-daun di sekitar mereka yang menemani percakapan mereka.
"Haha, siapa sangka kita bakal ketemu lagi dalam situasi begini, ya, Mas?" Wira berkata dengan tawa ringan, menghisap rokoknya dan menghembuskan asap ke udara. Ia merasa sedikit lebih santai setelah makan bersama Gendis dan keluarga.
Cakra terkekeh, menatap Wira dengan senyum tipis. "Iya, dunia ini memang sempit, ya. Tapi aku senang banget kalau ternyata kamu orangnya," jawab Cakra, suaranya penuh kehangatan meskipun terdengar santai. Cakra sudah mengenal Wira cukup lama—walaupun jarang berjumpa, ia bisa merasakan karakter pria ini, dan itu membuatnya merasa lebih nyaman.
Wira tersenyum, tampak sedikit terharu dengan sambutan Cakra. "Aku juga nggak nyangka bisa datang ke sini," katanya, masih sedikit mengalihkan pandangannya, mencoba menenangkan perasaan yang mulai muncul setelah makan siang tadi. "Tapi ya, ini kesempatan, Mas. Aku nggak mau sia-siakan."
Cakra mengangguk pelan, matanya menatap lurus ke depan. "Kamu pasti nggak cuma main-main, kan?" tanya Cakra, lebih kepada untuk memastikan apa yang ada di hati Wira.
Wira menatap Cakra dengan serius, seolah menjawab bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan keyakinan yang datang dari dalam dirinya. "Saya nggak main-main, Mas. Ganes itu luar biasa. Saya pengen banget ada di hidup dia, nggak cuma sebagai teman, tapi sebagai seseorang yang bisa dia andalkan," jawabnya dengan jujur, tatapannya tak pernah lepas dari Cakra.
Cakra menarik napas panjang dan menghisap rokoknya. Sesaat ia terdiam, merasakan kata-kata Wira yang terdengar tulus. "Kalau kamu serius, ya, Wir," kata Cakra sambil melemparkan senyum tipis, "jangan sampai Ganes kecewa. Kami udah cukup banyak melihat orang datang dan pergi dalam hidupnya. Jadi pastikan kamu ada di sana, bukan hanya saat mudah, tapi juga saat susah."
Wira mengangguk, kali ini matanya menunjukkan ketegasan. "Saya ngerti, Mas. Saya siap untuk itu. Saya nggak akan pergi, dan saya akan pastiin Ganes nggak pernah merasa sendirian."
Cakra tersenyum lebih lebar. "Bagus. Kalau kamu serius, kami akan mendukung. Tapi kamu juga harus siap dengan segala yang ada, nggak cuma senangnya aja."
"Siap, Mas. Saya tahu Ganes bukan cuma perempuan yang saya suka. Dia ibu dari Amika juga, dan itu tanggung jawab besar," jawab Wira dengan tekad yang semakin kuat di suaranya.
Cakra mengangguk puas, merasa lebih yakin dengan Wira. "Oke, kalau begitu, kita lihat aja nanti. Tapi jangan buat aku kecewa, ya, Wir."
Wira tersenyum lebar, melemparkan pandangan penuh rasa terima kasih kepada Cakra. "Nggak akan, Mas. Terima kasih sudah percaya."
Suasana di teras terasa lebih hangat setelah percakapan ini, meski hanya ada dua pria yang berbicara dengan santai, tapi kedekatan dan pemahaman mereka terasa nyata. Saling mengerti, meskipun ada banyak hal yang masih harus mereka jalani bersama.
...
Setelah Wira, Ganes, dan Amika pulang, Gendis berdiri diam di dekat jendela, matanya mengikuti mobil mereka yang menjauh dari halaman rumah. Perasaannya masih campur aduk, seolah masih ada banyak pertanyaan yang menggantung di udara.
Dia ingin percaya, tetapi ada bagian dari dirinya yang masih ragu. Apa yang membuatnya merasa begitu cemas? Apakah itu hanya naluri seorang kakak yang selalu ingin melindungi adiknya? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang masih mengganjal?
Cakra yang melihat istrinya begitu terlarut dalam pikirannya, menghampiri dengan langkah ringan. Tanpa banyak bicara, ia menepuk pundak Gendis, memberikan rasa tenang dengan kehadirannya. "Dia orang baik, Dek," katanya dengan nada penuh keyakinan, suara lembut namun penuh makna. "Mas udah kenal dia hampir sepuluh tahun. Dia pria baik, mapan, dan—jujur aja—ganteng juga. Kalau Mas sih seneng banget kalau Ganes berjodoh sama Wira."
Gendis menoleh ke arah Cakra, sedikit terkejut mendengar perkataan suaminya yang agak santai, meskipun penuh kebijaksanaan. Ia menghembuskan napas panjang, kemudian menunduk sejenak, berusaha mencerna semuanya.
"Mas, aku... aku juga merasa dia bukan orang sembarangan," jawab Gendis, suaranya lebih pelan, namun ada rasa hangat yang mulai menyelinap ke dalam hatinya. "Wira... dia bicara dengan ketulusan. Cara dia menatap Ganes, cara dia menyayangi Ami. Aku bisa merasakannya, tapi tetap saja... aku masih khawatir."
Cakra tersenyum lembut, meletakkan tangannya di punggung Gendis, seolah memberikan dukungan tak terucapkan. "Gendis, kadang kita memang harus melepaskan sedikit kekhawatiran kita, memberi ruang untuk kebahagiaan mereka. Ganes sudah dewasa, dan dia berhak memilih jalannya sendiri. Kamu sebagai kakak pasti selalu ada untuk dia, tapi kita juga harus percaya pada keputusan adik kita, kan?"
Gendis mengangguk perlahan. Kata-kata Cakra menyentuh hati, mengingatkannya bahwa meskipun ia ingin selalu melindungi Ganes, ia juga harus memberi ruang bagi adiknya untuk tumbuh dan membuat keputusan untuk dirinya sendiri.
"Tapi kalau nanti dia terluka..." Gendis berbicara pelan, lebih kepada dirinya sendiri.
Cakra menatap Gendis dengan penuh pengertian. "Kita akan ada di sana untuk dia, Dek. Kita akan selalu ada."
Gendis mengangguk lagi, kali ini lebih tegas. Matanya menatap ke luar jendela, menyaksikan mobil yang semakin jauh. Mungkin ini saatnya ia memberikan kepercayaan, memberikan ruang bagi adiknya untuk melangkah ke depan, sambil tetap berada di belakangnya, siap memberikan dukungan penuh.
Dan untuk pertama kalinya, Gendis merasa sedikit lebih ringan. Mungkin—hanya mungkin—ini adalah awal dari sesuatu yang baik.
0 notes
Text
XIII. Tak Ada Jalan untuk Mundur

Rumah terasa begitu sunyi malam itu, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan menemani. Di sofa ruang tamu, Wira tertidur pulas dengan Ami yang menyender di dadanya, tubuh mungilnya nyaman berada di pangkuan pria itu. Mereka baru saja menyelesaikan beberapa buku cerita sebelum akhirnya lelah dan terlelap begitu saja.
Ganes tersenyum kecil melihat pemandangan itu—sesuatu yang terasa begitu alami, begitu hangat. Hatinya berdesir saat melihat bagaimana Wira memeluk Ami dalam tidurnya, seperti seseorang yang telah lama menjadi bagian dari keluarga mereka.
Dengan hati-hati, ia menggendong Ami dan membawanya ke kamar. Gadis kecil itu menggumam pelan dalam tidurnya sebelum kembali terlelap di tempat tidurnya yang empuk. Ganes membenarkan selimutnya, mengecup keningnya sebentar, lalu kembali ke ruang tamu.
Saat ia kembali, Wira masih tertidur di sofa, napasnya teratur, ekspresi wajahnya terlihat begitu tenang. Ganes duduk di sebelahnya, membiarkan dirinya menikmati momen ini lebih lama.
Tatapannya jatuh pada kacamata yang masih bertengger di wajah Wira. Dengan lembut, ia melepaskannya dan meletakkannya di atas meja. Kini, tanpa halangan, ia bisa melihat wajah pria itu lebih dekat—garis rahangnya yang tegas, hidungnya yang lurus, alis yang sedikit berkerut dalam tidur, dan bibirnya yang sedikit terbuka.
Hatinya bergetar.
Sejak kapan Wira menjadi bagian dari dunianya? Dari dunianya dan Ami?
Jari-jarinya hampir terulur untuk menyentuh wajah Wira, tapi ia ragu. Ini bukan pertama kalinya ia menyadari betapa hatinya telah tertambat pada pria itu, tapi ini adalah pertama kalinya ia mengizinkan dirinya untuk benar-benar tenggelam dalam perasaan itu.
Namun, tepat saat ia masih menatap Wira dari jarak begitu dekat, mata pria itu terbuka.
Ganes membeku.
Tatapan mereka bertemu dalam keheningan yang mendebarkan. Ganes bisa merasakan panas merayap ke wajahnya, tersadar bahwa ia tertangkap basah memperhatikan Wira dengan terlalu intens.
Namun, Wira tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya, dalam dan lekat, seolah sedang membaca sesuatu di dalam dirinya.
Dan sebelum Ganes bisa bergerak atau mengatakan sesuatu untuk menghindari situasi ini, Wira mengangkat tangannya, menempelkan telapak tangannya yang besar dan hangat ke pipi Ganes.
Dada Ganes semakin sesak.
Jari-jari Wira mengusap kulitnya pelan, membelai lembut seakan memastikan bahwa Ganes benar-benar ada di hadapannya, bukan sekadar ilusi. Dan dalam gerakan yang lambat namun pasti, Wira mencondongkan tubuhnya, mendekatkan wajahnya ke wajah Ganes.
Seketika, dunia Ganes berhenti berputar.
Bibir Wira menyentuh bibirnya. Lembut, hangat, dan membuat seluruh tubuhnya bergetar.
Oh, tidak...
Jantungnya berdegup kencang. Ia bisa merasakan napas hangat Wira yang terhembus di kulitnya, membuat tubuhnya terasa lemas. Ia seharusnya menolak, seharusnya menjauh, tapi yang terjadi justru sebaliknya.
Ganes memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam ciuman itu.
Wira menarik tubuhnya lebih dekat, lengannya yang kuat melingkari pinggang Ganes dengan erat, seakan tak ingin melepaskannya. Bibirnya bergerak perlahan, mengecup, melumat dengan penuh kelembutan, namun juga menyiratkan sesuatu yang lebih dalam—sesuatu yang selama ini ia tahan, sesuatu yang selama ini ia sembunyikan.
Dan Ganes membalasnya.
Membalas dengan penuh perasaan.
Hatinya membuncah, tenggelam dalam emosi yang begitu intens, begitu lembut, namun juga begitu menggetarkan. Ia bisa merasakan debaran jantung Wira yang berpacu seirama dengan miliknya.
Saat mereka akhirnya berpisah, napas mereka masih tersengal. Wira tetap menatapnya, ibu jarinya mengusap pipi Ganes dengan penuh kelembutan.
Lalu, dengan suara yang rendah dan serak, Wira berbisik sesuatu yang membuat Ganes semakin jatuh cinta.
"Jangan lagi menjauh dariku."
Tak ada jalan untuk mundur.


0 notes
Text
XII. Kopi, Tulisan, dan Kejutan Kecil

Pagi itu, kafe tempat Ganes bekerja sedikit lebih ramai dari biasanya. Biji kopi baru baru saja datang, dan Ganes sedang sibuk meracik espresso ketika pintu kafe terbuka, disertai suara lonceng kecil yang berdenting.
"Pagi, Mas Wira," sapa Ganes tanpa menoleh, sudah hafal langkah kaki yang baru masuk.
"Pagi, Ganes." Suara itu terdengar akrab, lembut, dan seperti biasa, membawa ketenangan tersendiri.
Ganes tetap fokus pada pekerjaannya. "Mas Wira mau kopi apa hari ini?" tanyanya sambil menuangkan susu ke dalam cangkir espresso.
"Cappuccino, kalau bisa yang spesial."
Ganes melirik sekilas. "Semua kopi yang aku buat spesial."
"Iya, aku tahu." Wira tersenyum kecil, lalu duduk di kursi bar di depan meja kerja Ganes, mengamatinya bekerja.
Setelah cappuccino selesai, Ganes menyodorkan cangkir itu kepadanya. Wira menatap permukaan kopi yang dihiasi latte art berbentuk hati.
Ia tersenyum sekilas, lalu berkata santai, "Bentuk hatinya sengaja, ya?"
Ganes meliriknya sekilas sebelum menjawab datar, "Itu kebiasaan tanganku aja."
"Oh." Wira tidak bertanya lebih lanjut, hanya meniup pelan cappuccinonya sebelum menyeruputnya.
Ganes kembali melanjutkan pekerjaannya, tapi ia tahu Wira masih duduk di sana.
"Lagi nulis apa sekarang?" tanya Wira kemudian, seperti biasa ingin tahu tentang pekerjaan menulis Ganes.
"Artikel parenting, tentang tantrum anak balita."
Wira mengangguk mengerti. "Oh, pengalaman pribadi?"
Ganes menghela napas panjang. "Banget. Ami kemarin nangis gara-gara aku motong rotinya miring."
Wira diam sejenak sebelum berkomentar, "Ami tahu apa yang dia mau, itu bagus."
Ganes tertawa kecil, merasa lucu mendengar jawaban Wira yang selalu berusaha melihat sisi positifnya. "Mas Wira, kalau punya anak nanti, bakal pusing juga."
Wira tersenyum kecil. "Mungkin pusing, tapi... nggak masalah kalau memang berharga."
Ganes terdiam sejenak, mendengar nada serius di balik kata-kata itu. Tapi sebelum ia bisa membalas, pelanggan lain datang, membuatnya harus kembali fokus bekerja.
Esoknya adalah hari libur Ganes dari kafe, tapi bukan berarti ia bisa bersantai sepenuhnya. Pekerjaan menulis masih menunggu, dan yang lebih penting—Ami sedang super aktif sejak pagi.
Ganes baru saja selesai menidurkan Ami untuk tidur siang ketika ponselnya berbunyi. Nama Mas Wira muncul di layar.
"Halo, Mas?" Ganes menjawab pelan agar tidak membangunkan Ami.
"Ganes, aku di depan rumah."
Ganes mengernyit. "Hah? Ngapain?"
"Buka dulu, deh."
Dengan bingung, Ganes melangkah ke depan dan membuka pintu. Di sana, berdiri Wira dengan dua kantong kertas di tangannya dan senyum kecil di wajahnya.
"Bawain kopi buat Mamah Ganes yang sibuk."
Ganes melipat tangan di dada. "Mas Wira, ini rumah, bukan kafe. Mau pesananku, ya?"
Wira terkekeh. "Nggak, tenang. Aku sudah beli. Ini buat kamu, dan ini..." Ia mengangkat kantong satunya. "Buat Ami."
Seketika, terdengar suara kecil dari dalam rumah. "Wiwi!"
Ami yang seharusnya tidur, kini sudah berdiri di belakang Ganes dengan rambut berantakan dan piyama panda kesukaannya.
Ganes menghela napas. "Astaga, ini pasti karena suara Mas Wira, kan."
Wira menyeringai. "Aku memang berbakat bikin orang bangun."
Ami menghampiri mereka dengan mata berbinar melihat kantong yang dipegang Wira. "Apa itu? Apa itu?"
"Buat Ami," kata Wira sambil berjongkok, menyerahkan kantongnya.
Ami mengambilnya dengan antusias dan langsung mengeluarkan isinya—roti panggang yang dipotong rapi.
Ganes menatap Wira curiga. "Kenapa kayaknya rapi banget?"
Wira menatap ke samping. "Ehm... aku latihan semalaman."
Ganes tertawa. "Jangan bilang gara-gara Ami ngamuk waktu aku motong roti miring kemarin?"
Wira menghela napas dramatis. "Aku orang yang belajar dari kesalahan. Sekarang aku sudah lulus ujian memotong roti balita."
Ami menggigit rotinya dengan puas, lalu menatap Wira dengan ekspresi polos. "Wiwi bisa buat roti?"
Wira menyeringai, mencoba terlihat keren. "Tentu. Wiwi bisa bikin roti, bisa bikin kopi—"
"Bisa masak?" potong Ganes, menantang.
Wira terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, "Bisa... masak air."
Ganes mendengus geli. "Pantes sering makan di luar."
Tapi sebelum mereka bisa bercanda lebih jauh, Ami tiba-tiba berkata dengan suara riang, "Makasih, Papah!"
Hening, namun kemudian mereka tersenyum bersama.

0 notes
Text
XI. Sebuah Kata Baru

POV Ganes:
Ami tumbuh menjadi anak yang semakin pintar dan penasaran. Setiap hari, ia belajar sesuatu yang baru—baik dari buku cerita yang dibacakan Ganes sebelum tidur, dari taman bermain, atau dari tontonan anak-anak di televisi. Namun, di balik senyum dan tawa kecilnya, ada rasa penasaran yang sulit diungkapkan— yaitu rasa penasaran pada sosok yang tak pernah ia kenal dengan sempurna: Papah.
Hari itu, Ganes duduk di sofa, memeluk Ami yang tertidur di pangkuannya. Mereka baru saja membaca buku cerita tentang seekor kelinci kecil yang tersesat di hutan, dan di akhir cerita, kelinci itu diselamatkan oleh Papah kelinci yang kuat dan bijaksana. Ganes tersenyum lembut, merasakan kedamaian saat mengelus rambut Ami yang lembut.
"Papah kelinci datang menyelamatkan anaknya," Ganes membaca pelan, suara lembutnya mengalun di udara yang hening.
Ami, yang masih setengah terlelap, mendongak dengan mata yang masih setengah terpejam. Tanpa berpikir panjang, ia bertanya, "Papah itu apa, Mamah?" Suaranya belum begitu lancar, penuh rasa ingin tahu.
Ganes terdiam sejenak. Kata-kata itu mengusik hatinya, menggugah kenangan yang dalam dan sulit ia lupakan. Ia memandang wajah kecil Ami yang penuh dengan harapan dan ketulusan. Ganes berusaha menahan gejolak di dadanya, mencari cara untuk menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya paham.
"Papah itu… hmm, seperti Mamah, sayang, tapi laki-laki," jawab Ganes pelan, mencoba menyembunyikan rasa haru yang muncul begitu saja. "Papah itu orang yang sayang sama anaknya, menjaga, dan selalu ada untuk mereka."
Ami merenung, matanya yang besar berkedip-kedip, seakan mencoba memproses penjelasan itu. Lalu, dengan suara yang masih terdengar polos, ia bertanya lagi, "Papah itu... kayak Papah Vi?"
Ganes tersentak. Ia tahu, Kavindra adalah sosok yang hanya ada dalam foto, sosok yang dikenalkan kepada Ami melalui foto-foto yang sering mereka lihat bersama. Ganes menatap foto-foto itu, lalu kembali menatap mata penuh harapan milik Ami.
"Iya, sayang... Papah Vi juga begitu," jawab Ganes dengan suara yang semakin lembut. "Papah Vi sayang banget sama Ami."
Namun, Ami tampaknya masih belum sepenuhnya mengerti. Dengan tatapan polos, ia bertanya lagi, "Wiwi... juga papah?"
Ganes menatap Ami sejenak, hatinya bergetar. Wira, yang selama ini hadir dalam hidup mereka, menjadi sosok yang mulai mengisi tempat kosong itu—tanpa bisa dihindari, tanpa bisa disangkal. Ganes merasa ada rasa yang berbeda tumbuh dalam hatinya setiap kali Wira ada di sekitar mereka.
Dengan suara hati yang terdalam, Ganes menjawab, "Wiwi baik ya sama Ami? Dia juga sayang sama Ami, jagain Ami, dan selalu ada untuk Ami."
Ami mengangguk, tampaknya puas dengan penjelasan itu. "Wiwi baik." Suaranya begitu polos, begitu murni.
Ganes menatapnya dalam-dalam, perasaan hangat dan pilu menyatu di dadanya. Betapa besar pengaruh Wira dalam hidup mereka. Satu hal yang pasti: Wira sudah menjadi bagian dari dunia Ami dan Ganes, tanpa mereka sadari.
...
POV Wira:
Hari itu, seperti biasa, Wira datang menemui mereka di taman. Ami, yang sejak tadi asyik bermain dengan boneka pandanya, langsung bersinar wajahnya begitu melihat sosok yang akrab baginya.
"Wiwi!" serunya riang, berlari kecil menghampiri pria itu.
Wira tersenyum lebar, jongkok menyambut Ami, lalu mengeluarkan kejutan kecil dari belakang punggungnya—balon kelinci berwarna merah muda. "Ini buat Ami," ucapnya, menyerahkan balon itu.
Ami menatap balon itu dengan mata berbinar, tetapi bukan balon itu yang membuatnya begitu bahagia. Ia tidak langsung mengambilnya. Sebaliknya, ia melangkah lebih dekat, lalu tiba-tiba memeluk Wira erat, lebih erat dari biasanya.
"Makasih, Papah."
Waktu seakan berhenti.
Wira membeku, tangan yang memegang balon sedikit gemetar. Ganes, yang baru saja tiba sambil membawa dua cup minuman, terhenti di tempatnya. Matanya membulat, seolah tak yakin dengan apa yang baru ia dengar.
"Ami..." Ganes berusaha berkata sesuatu, tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan.
Namun, Ami tidak menyadari keterkejutan di sekelilingnya. Ia hanya tersenyum lebar, kepalanya masih bersandar di bahu Wira, memeluknya dengan nyaman, seolah tempat itu memang seharusnya menjadi tempatnya sejak dulu.
"Papah Wiwi," katanya lagi, kali ini lebih jelas, lebih yakin.
Jantung Wira berdebar begitu kencang. Tangannya perlahan membalas pelukan Ami, meski dalam hatinya ada begitu banyak emosi yang bercampur aduk. Ia menatap Ganes, mencari jawaban, tetapi Ganes pun tampak tak tahu harus berkata apa.
Ganes menelan ludah, matanya mulai terasa panas. Ia melangkah maju, duduk berjongkok di samping mereka, lalu membelai rambut Ami dengan lembut. "Sayang, kenapa manggil Wiwi ‘Papah’?" tanyanya pelan, suaranya hampir bergetar.
Ami menatap ibunya dengan polos, masih dalam dekapan Wira. "Wiwi kayak Papah kelinci. Wiwi papah Ami"
Hati Ganes mencelos.
"Wiwi gendong Ami, jagain Ami, peluk Ami. Wiwi juga jagain Mamah," lanjut Ami dengan polosnya. Lalu, dengan ekspresi yang sangat tulus, ia menambahkan, "Wiwi kayak Papah, ya?"
Air mata hampir jatuh dari pelupuk mata Ganes. Ia mengangguk pelan, mencoba tersenyum meski dadanya terasa sesak. "Iya, sayang... Wiwi juga sayang sama Ami, seperti Papah Vi dan Papah kelinci."
Wira masih belum bisa berkata apa-apa. Napasnya terasa berat, dadanya dipenuhi perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia melihat Ganes—wanita yang selama ini mengisi pikirannya—dan kemudian melihat Ami, anak kecil yang tanpa ragu telah memberinya tempat di hatinya.
Tanpa sadar, Wira mengusap punggung kecil Ami dengan lembut. Lalu, dengan suara yang penuh kehangatan, ia berbisik, "Terima kasih, Ami."
Mungkin, ini adalah saat di mana dunianya berubah selamanya.
Ganes menunduk, menggenggam tangan kecil Ami yang masih melingkari leher Wira. Ada ketakutan dalam hatinya, ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi lebih dari itu—ada rasa syukur.
Karena di momen itu, ia tahu.
Ami telah menemukan sosok yang selama ini ia cari. Dan mungkin, tanpa mereka sadari, mereka bertiga telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar perasaan.
Mereka telah menjadi keluarga.
0 notes
Text
X. Wiwi, Aku Sayang!

Hari Minggu ini, Wira menemani Ganes dan Ami jalan-jalan ke taman. Rencana awalnya sederhana: membiarkan Ami bermain di playground sementara Ganes dan Wira duduk santai. Tapi tentu saja, bersama balita seaktif Ami, rencana hanya tinggal rencana.
"Wiwi! Ayo ke sana!" Ami menarik tangan Wira dengan semangat, menunjuk ke perosotan berwarna merah.
Wira mengangkat alis. "Loh, kan Ami sudah besar, bisa main sendiri."
Ami menggeleng cepat. "Wiwi ikut! Wiwi main!"
Ganes, yang duduk di bangku taman sambil menyeruput kopi, terkekeh. "Mas Wira, nggak berani naik perosotan, ya?" godanya.
Wira mendengus. "Hei, aku sudah besar. Itu perosotan buat anak-anak."
Tapi sebelum Wira bisa mengelak lebih jauh, Ami sudah menarik tangannya lebih kuat. "Wiwi takut?" tanyanya polos.
Wira mendesah, menyerah. "Baiklah, baiklah. Wiwi ikut."
Dengan enggan, ia menaiki tangga kecil di belakang Ami. Balita itu sudah duduk manis di atas perosotan, menatap Wira penuh semangat. "Wiwi duduk!"
Wira menatap sekeliling. Ada beberapa ibu-ibu di taman yang meliriknya sambil tersenyum geli. Tapi demi Ami, ia menyingkirkan rasa malunya dan duduk di perosotan sempit itu.
"Siap, Ami?" tanyanya, pura-pura keren.
Ami mengangguk. "Wiwi juga harus bilang!"
Wira menghela napas, lalu berkata, "Oke! Satu, dua, tig—"
"Wiwi dorong!"
Sebelum Wira menyelesaikan hitungan, Ami sudah menggunakan kedua kakinya yang mungil untuk mendorong Wira lebih dulu.
"WOA—"
Gubraaaak!
Wira, yang jelas-jelas lebih besar dari target pengguna perosotan itu, meluncur ke bawah dengan posisi tidak seimbang. Alih-alih mendarat dengan anggun seperti Ami, ia malah jatuh terduduk di atas pasir dengan ekspresi terkejut.
Ganes terbatuk menahan tawa. Beberapa anak kecil di sekitar ikut tertawa geli melihat "orang besar" terjungkal begitu saja.
Ami berlari ke arah Wira dan bertepuk tangan. "Wiwi jatuh! Hahaha!"
Wira memandang Ami dengan wajah setengah kesal, setengah pasrah. "Ami, Wiwi sakit..."
Ami menghentikan tawanya, menatap Wira sebentar, lalu tanpa diduga, ia langsung merangkul Wira kecil-kecil dan mencium pipinya sekilas. "Wiwi nggak sakit. Aku sayang!"
Hening.
Ganes, yang tadinya masih menahan tawa, kini mendadak terdiam.
Wira juga sama sekali tidak bergerak. Ia hanya menatap Ami yang tersenyum manis, seolah hal itu adalah hal paling wajar di dunia.
Ganes mengerjapkan mata. "Ami... tadi bilang apa?"
Ami mengulang dengan polos. "Aku sayang Wiwi!"
Wira menelan ludah. Jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas.
Ganes menghela napas, berusaha mengontrol emosinya. "Ami... tahu nggak, kata itu spesial?"
Ami mengangguk kecil. "Iya. Aku bilang ke Mamah. Ke Wiwi juga!"
Ganes menatap Wira yang masih terdiam. Tatapannya penuh arti, seolah berkata, Mas Wira, hati kamu masih aman?
Wira akhirnya mengembuskan napas, lalu tersenyum kecil. Ia mengusap kepala Ami dengan lembut.
"Wiwi juga sayang Ami."
Dan entah kenapa, saat mengucapkan itu, rasanya seperti sebuah kepastian yang tidak bisa dihindari.
...
Sejak pertama kali bertemu Ami, Wira tahu bahwa ia adalah anak yang istimewa. Bukan hanya karena matanya yang besar dan penuh rasa ingin tahu, atau tawanya yang mudah pecah seperti lonceng kecil yang menggema. Tapi karena Ami, tanpa sadar, telah mengubah sesuatu di dalam dirinya.
Awalnya, Wira hanya ingin menjadi teman bagi Ganes dan Ami. Tak lebih. Ia tahu batasannya. Ia tahu bahwa Ami memiliki sosok "Papah" dalam foto yang selalu dielus jemari mungilnya sebelum tidur. Ia tahu bahwa Ganes telah membangun dunianya sendiri, sebuah dunia yang tidak perlu diusik oleh seseorang sepertinya.
Tapi perlahan-lahan, kehadiran Ami mulai melekat di dalam pikirannya, di dalam hatinya.
Setiap kali Ami tertawa karena hal kecil—entah karena Wira membelikan es krim, menggendongnya tinggi-tinggi, atau sekadar menggambar panda dengan bentuk yang jelek di kertas gambarnya—Wira merasa seolah ia melakukan sesuatu yang benar.
Setiap kali Ami berlari ke arahnya dengan tangan terulur, tanpa ragu, tanpa takut, Wira merasa ada sesuatu yang hangat mengalir dalam dirinya.
Dan hari itu, di taman, ketika Ami memeluknya dan berkata, "Aku sayang Wiwi!"—itu adalah titik di mana Wira menyadari sesuatu.
Bahwa meskipun Ami bukan darah dagingnya, ia tetap ingin melindungi gadis kecil itu.
Bahwa meskipun ia tidak pernah berencana untuk mencintai seorang anak, Ami telah mengajarinya bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat.
Wira duduk di tepi tempat bermain, mengawasi Ami yang berlarian dengan lincah. Ia masih bisa merasakan pelukan kecil itu, suara polos yang mengucapkan kata "sayang" tanpa keraguan sedikit pun.
Di sebelahnya, Ganes duduk diam sambil menggenggam gelas kopi yang sudah hampir habis.
"Mas Wira kenapa diam?" tanyanya pelan.
Wira menoleh, tersenyum tipis. "Nggak. Cuma kepikiran sesuatu."
Ganes menaikkan alisnya. "Apa?"
Wira menatap Ami yang sedang mengejar seekor kupu-kupu, tertawa lepas.
"Aku sayang Ami," jawabnya jujur.
Ganes terdiam.
"Aku tahu dia bukan anakku. Dan mungkin aku nggak punya hak buat merasa seperti ini. Tapi... aku ingin selalu ada buat dia."
Ganes menatapnya, dan untuk pertama kalinya, Wira melihat sesuatu yang berbeda dalam matanya. Sesuatu yang lebih dalam.
Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ia tidak tahu apakah ia bisa menjadi bagian dari hidup Ganes dan Ami selamanya.
Tapi untuk saat ini, satu hal yang pasti:
Ami telah menjadi bagian dari hatinya, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri lagi.
0 notes
Text
IX. Kenangan yang Tak Akan Pernah Hilang
POV Ganes:
Ganes duduk di tepi tempat tidur, jari-jarinya dengan lembut menyentuh bingkai foto di nakas. Foto itu sudah sedikit pudar, tetapi senyuman Kavindra tetap terlihat jelas di sana. Senyum yang dulu selalu menyambutnya setiap pagi, yang membuat dunia terasa lebih ringan meski hidup tak selalu mudah.
Ada banyak hal yang sudah berubah sejak kepergian Kavindra. Waktu berlalu, luka yang dulu terasa begitu dalam kini perlahan menjadi bagian dari dirinya. Bukan berarti ia melupakan, bukan berarti rasa kehilangan itu sirna—hanya saja, ia belajar untuk menerima.
Kavindra adalah lelaki yang begitu tulus mencintainya. Sejak mereka bertemu, Ganes tahu bahwa pria itu berbeda. Ia tidak hanya datang membawa janji, tetapi juga kepastian. Ia adalah tempat pulang, tempat di mana Ganes bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi.
Bersama Kavindra, hidup terasa lebih mudah.
Ia ingat bagaimana suaminya selalu menggenggam tangannya erat setiap kali mereka berjalan berdampingan. Bagaimana suara tawanya memenuhi ruangan ketika mereka mengobrol di malam hari. Bagaimana ia dengan sabar menemaninya melewati masa-masa sulit, meyakinkan bahwa apa pun yang terjadi, mereka akan baik-baik saja.
Dan yang paling Ganes ingat adalah ekspresi wajah Kavindra saat pertama kali melihat Ami lahir ke dunia. Mata yang penuh haru, senyum yang dipenuhi rasa syukur. Ia mengusap kepala bayi kecil mereka dengan hati-hati, seakan takut membuatnya terluka.
"Dia mirip kamu," bisiknya saat itu, matanya berbinar.
Tapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama.
Kecelakaan itu merenggut Kavindra dari hidup mereka, meninggalkan Ganes dengan rasa sakit yang sulit diungkapkan. Ia kehilangan seorang suami, seorang sahabat, seorang pria yang selalu ada di sisinya tanpa ragu.
Namun, seiring waktu, Ganes menyadari sesuatu—Kavindra mungkin sudah tiada, tapi cinta dan kenangan mereka tidak akan pernah hilang.
Ia ingin Ami mengenal ayahnya, meski hanya lewat foto dan cerita. Ia ingin putrinya tahu bahwa ada seorang pria yang mencintainya bahkan sebelum ia lahir. Bahwa ada seseorang yang, meski tidak bisa hadir secara fisik, akan selalu menjadi bagian dari mereka.
Kini, hidupnya mulai berubah lagi. Ada Wira.
Dan meskipun hatinya perlahan mulai terbuka untuk pria itu, Kavindra tetap menjadi bagian dari dirinya. Ia bukan bayang-bayang yang harus dilupakan, bukan masa lalu yang harus ditinggalkan. Kavindra adalah salah satu cerita terindah dalam hidupnya—dulu, sekarang, dan bahkan nanti, ketika ia melangkah maju bersama Wira.
Karena cinta sejati tidak selalu berarti harus bertahan selamanya dalam bentuk yang sama. Kadang, cinta sejati adalah tentang mengenang dengan penuh syukur, tentang menerima bahwa cinta bisa tumbuh lagi, tanpa harus menggantikan yang pernah ada.
Ganes menghela napas pelan, mengusap lembut bingkai foto di tangannya.
"Terima kasih, Kavindra. Karena telah mencintaiku dengan begitu tulus."
Lalu ia tersenyum, bukan lagi dengan kesedihan, tetapi dengan rasa damai.
POV Wira:
Di makam...
Wira memandangi Ganes yang berdiri di sampingnya, tangan wanita itu menggenggam erat jemari kecil Ami. Mata Ganes terarah pada batu nisan di hadapan mereka, senyumnya lembut, penuh kehangatan meski ada raut kerinduan di sana.
Di sisi lain, Ami menatap foto di nisan itu dengan rasa ingin tahu. "Papah," gumamnya pelan, jemarinya menyentuh ukiran nama Kavindra Pradipta di batu marmer dingin.
Wira menarik napas panjang, merasakan kehadiran seseorang yang tak pernah ia temui tetapi begitu penting dalam hidup Ganes dan Ami. Ia tidak pernah melihat bagaimana Kavindra mencintai Ganes, tetapi ia bisa merasakannya. Bisa melihatnya dari cara Ganes mengenang pria itu—tanpa air mata berlebihan, tanpa kesedihan yang menenggelamkan, hanya dengan cinta yang tetap hidup dalam kenangan.
Dan justru itu yang membuat Wira semakin yakin pada perasaannya.
Karena seorang wanita yang bisa mencintai seperti itu… pasti juga bisa mencintai dirinya dengan ketulusan yang sama.
Ganes bukan seseorang yang melupakan masa lalunya demi masa depan, bukan juga seseorang yang membiarkan kesedihan mengurungnya. Ia adalah seseorang yang belajar menerima, yang melangkah maju tanpa menghapus jejak yang pernah ada.
Dan Wira ingin menjadi bagian dari langkah itu.
Ia berjongkok di samping Ami, mengusap punggung kecil gadis itu. "Ami tahu, Papah Kavindra pasti bangga melihat Ami tumbuh besar dan sehat."
Ami mengangguk kecil, lalu menoleh ke Ganes. "Mamah, Papah suka es krim nggak?" tanyanya polos.
Ganes terkekeh pelan, mengusap kepala putrinya dengan penuh kasih. "Papah suka banget. Kalau Ami makan es krim, Papah pasti ikut senang."
Wira tersenyum melihat interaksi itu. Ia tidak cemburu pada sosok yang telah tiada. Justru sebaliknya, ia ingin mengenal Kavindra lebih jauh—bukan sebagai saingan, tapi sebagai bagian dari kehidupan orang-orang yang ia cintai.
Ketika Ganes menoleh padanya, ada cahaya lembut di matanya. "Makasih ya, Mas, udah mau ke sini sama kami."
Wira menggeleng pelan. "Aku ingin jadi bagian dari hidup kalian, Nes. Itu berarti menerima semua yang ada di dalamnya—termasuk Kavindra."
Ganes terdiam sejenak, lalu tersenyum. Kali ini lebih dalam, lebih penuh makna.
Di bawah langit yang sedikit mendung, di depan nisan seorang pria yang pernah mencintai Ganes, Wira berjanji pada dirinya sendiri—ia akan menjaga wanita ini dan putrinya. Bukan untuk menggantikan, tapi untuk melanjutkan.
Karena cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang memahami dan menerima. Dan Wira siap untuk itu.
0 notes
Text
VIII. Pengakuan di Bawah Langit Senja

Langit sore mulai berubah warna, semburat jingga dan merah muda menghiasi cakrawala saat Wira dan Ganes berjalan berdampingan di taman. Ami berlari kecil di depan mereka, tertawa riang saat mengejar burung-burung kecil yang terbang rendah.
Ganes memperhatikan putrinya dengan senyum lembut. Ia merasa tenang hari ini, seperti semua kepenatan dunia menghilang begitu saja saat melihat Ami bahagia. Dan di sampingnya, ada Wira—seseorang yang belakangan ini selalu ada, selalu menawarkan kenyamanan tanpa banyak bicara.
“Kamu kelihatan capek, Nes,” suara Wira memecah keheningan di antara mereka.
Ganes menggeleng pelan. “Nggak kok, cuma… banyak yang kupikirkan.”
Wira meliriknya, lalu menarik napas dalam. Hari ini, ia sudah bertekad untuk mengatakan sesuatu. Sesuatu yang selama ini ia simpan, sesuatu yang perlahan tapi pasti semakin memenuhi hatinya.
Mereka berhenti di bawah pohon besar, memandangi Ami yang masih asyik bermain. Hembusan angin sore membuat rambut Ganes sedikit berantakan, dan tanpa sadar, Wira ingin mengingatnya seperti ini—di bawah cahaya senja, dengan senyum yang perlahan ia kenal lebih dalam.
“Ganes,” Wira akhirnya memanggil, suaranya lebih serius dari biasanya.
Ganes menoleh, sedikit terkejut dengan nada itu. “Kenapa, Mas Wira?”
Wira menatap matanya. Tidak ada kebimbangan kali ini, tidak ada keraguan.
“Aku suka sama kamu.”
Ganes membeku seketika. Ia menatap Wira, mencari tanda apakah pria itu serius atau hanya bercanda. Tapi Wira tidak tertawa. Matanya penuh ketulusan, penuh kejujuran yang tidak bisa diabaikan.
“Aku tahu, mungkin aku bukan orang pertama yang pernah ada di hati kamu. Aku juga tahu, ada bagian dalam hidupmu yang nggak bisa aku gantikan,” lanjut Wira, suaranya lembut, “tapi aku nggak mau menggantikan siapa pun. Aku cuma ingin ada di samping kamu, menjalani hari-hari ke depan bareng kamu… dan Ami.”
Ganes menelan ludah. Hatinya berdebar kencang, tetapi bukan karena gugup—melainkan karena perasaan yang selama ini ia coba abaikan mulai menemukan tempatnya.
“Mas Wira…” Ia membuka mulut, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan.
Wira tersenyum kecil, lalu melanjutkan, “Aku nggak minta jawaban sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu perasaanku. Aku ingin kamu tahu bahwa aku ada, dan aku nggak akan ke mana-mana.”
Ami tiba-tiba berlari mendekat, tangannya terangkat meminta digendong. Ganes refleks mengangkat putrinya, sementara Ami tertawa kecil, memandangi Wira dengan mata berbinar.
“Wiwi!” seru Ami riang, tangannya terulur seolah ingin menyentuh Wira.
Wira tertawa kecil, mengusap kepala gadis kecil itu dengan lembut.
Ganes menatap keduanya—Ami yang semakin dekat dengan Wira, dan Wira yang selalu sabar, selalu hadir. Dan di dalam hatinya, ia tahu, mungkin selama ini ia memang mulai membuka diri untuk pria ini.
Mungkin, Wira adalah seseorang yang dikirimkan untuknya.
Mungkin, ia bisa bahagia lagi.

1 note
·
View note
Text
VII. Bertemu dengan Ami
POV Ganes:
Sore itu, rumah Gendis dipenuhi suara tawa anak-anak. Raka dan Riki sedang bermain mobil-mobilan, sementara Amika sibuk menumpuk balok kayu di dekat mereka. Ganes duduk di ruang tamu, menyeruput teh yang disiapkan Gendis.
Gendis melirik adiknya yang tampak ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi masih menimbang-nimbang kata-katanya. Sebagai kakak, ia mengenal Ganes lebih dari siapa pun.
"Kamu kenapa, Nes?" tanya Gendis akhirnya, meletakkan gelasnya ke meja.
Ganes menghela napas, memainkan ujung rambutnya yang tergerai di bahu. "Aku... ada seseorang yang mulai dekat denganku."
Gendis terdiam sejenak. Matanya menajam, naluri protektifnya langsung muncul. "Seseorang? Maksudnya... laki-laki?"
Ganes mengangguk pelan. "Namanya Wira. Dia pelanggan tetap di kafe. Kami sering mengobrol, dan dia baik... perhatian. Rasanya aku mulai nyaman dengannya."
Gendis menatap Ganes lama. Ia tidak ingin gegabah merespons, tapi hatinya penuh dengan kecemasan. Setelah semua yang dialami Ganes, setelah kehilangan Kavindra, Gendis takut adiknya akan terluka lagi.
"Tapi, Nes..." suara Gendis lebih lembut kali ini, "Kamu yakin dia orang yang baik?"
Ganes tersenyum tipis. "Aku belum tahu banyak tentang dia, Kak. Tapi dia tahu tentang Amika sejak awal, dan dia tidak menjauh. Malah, dia makin dekat. Dia... membuatku merasa dihargai, bukan hanya sebagai seorang ibu, tapi juga sebagai seorang wanita."
Gendis menatap Ganes dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu betapa sulitnya bagi adiknya untuk membuka hati lagi.
"Kak," lanjut Ganes pelan, "Aku nggak tahu apakah ini akan bertahan lama atau tidak. Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin bahagia lagi."
Gendis menarik napas dalam, lalu menggenggam tangan Ganes. "Aku hanya ingin kamu bahagia, Nes. Kalau kamu yakin, aku akan selalu mendukungmu. Tapi kalau dia menyakitimu..."
Ganes terkekeh. "Kakak bakal turun tangan?"
Gendis tersenyum, meski matanya masih menyiratkan kekhawatiran. "Tentu. Aku dan Mas Cakra pasti bakal lindungin kamu."
Ganes mengangguk pelan, merasa hangat oleh dukungan kakaknya. Ia tahu, apa pun yang terjadi nanti, Gendis akan selalu ada untuknya.
Pada malam hari, di kamar Ganes dan Amika...
Ganes duduk di tepi tempat tidur, mengusap pelan punggung kecil Amika yang mulai terlelap dalam dekapannya. Cahaya lampu tidur menerangi wajah mungil putrinya, memberikan kesan damai yang selalu membuat hati Ganes luluh.
"Ami sayang… besok kamu akan ketemu Om Wira," bisiknya lembut, meski ia tahu Amika mungkin sudah hampir tertidur dan tidak sepenuhnya memahami kata-katanya.
Ganes tersenyum tipis, membayangkan pertemuan itu. Ada perasaan harap, gugup, dan sedikit takut di hatinya.
"Mamah nggak tahu gimana reaksi Ami nanti, tapi Mamah ingin kamu tahu satu hal. Mamah nggak akan pernah membawa seseorang ke dalam hidup kita kalau Mamah nggak yakin dia orang baik."
Ia menarik napas panjang, membelai rambut Amika dengan penuh kasih. "Om Wira… dia baik, sayang. Mamah nggak tahu ke depannya akan seperti apa, tapi Mamah berharap… Ami bisa suka sama Om Wira, seperti Om Wira menyayangi Ami."
Ganes menatap wajah kecil putrinya. "Mamah ingin Ami tetap bahagia. Mamah ingin Ami tahu bahwa walaupun Papah nggak ada di sini lagi, selalu ada orang-orang yang akan menyayangi kita. Dan kalau suatu saat nanti Om Wira jadi bagian dari hidup kita… Mamah harap Ami bisa menerimanya dengan hati yang sama tulusnya seperti Mamah menerima Om Wira."
Amika bergerak sedikit dalam tidurnya, bibir mungilnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Ganes tersenyum, lalu mengecup kening putrinya.
"Apa pun yang terjadi nanti, Mamah hanya ingin yang terbaik untuk Ami. Dan Mamah akan selalu ada untukmu."
Di dalam hatinya, Ganes berdoa agar pertemuan besok berjalan dengan baik. Agar Amika bisa merasakan ketulusan yang Ganes rasakan dari Wira. Dan agar kebahagiaan yang perlahan datang dalam hidup mereka bisa terus bertumbuh.
POV Wira:
Keesokan harinya...
Hari ini, Wira bangun dengan perasaan yang campur aduk. Semangat, gugup, dan sedikit cemas bercampur menjadi satu. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri.
Hari ini aku akan bertemu Ami.
Anak Ganes.
Sudah beberapa hari sejak percakapannya dengan sang ibu, dan kini, Wira mengambil langkah pertamanya untuk mengenal lebih jauh dunia Ganes—dan dunia Ami.
Ia meraih kemeja putih favoritnya, lalu mengernyit. Terlalu formal? Ia ingin terlihat rapi, tapi tidak kaku. Akhirnya, ia memilih kaus lengan pendek warna biru tua dan celana jeans yang nyaman.
Saat memakai jam tangannya, ponselnya berbunyi.
Ganes: Mas Wira, nanti ketemu di taman aja ya. Ami suka main di sana.
Wira tersenyum kecil. Ia bisa membayangkan seorang anak kecil berlarian di antara ayunan dan perosotan, tertawa riang.
Sebelum berangkat, ia mengambil satu kantong kertas dari meja. Isinya? Boneka panda kecil dan beberapa camilan anak-anak. Kata Ganes, Ami terobsesi dengan panda.
"Semoga Ami suka."
Dengan napas panjang, Wira keluar dari apartemennya. Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar.

Di taman...
Wira duduk di bangku taman, merasa sedikit kaku. Di sampingnya, Ganes sedang membuka bungkus es krim untuk Ami, yang duduk di pangkuannya sambil menggoyang-goyangkan kakinya.
“Pelan-pelan, sayang,” Ganes mengingatkan saat Ami dengan antusias menyambar es krim itu dan langsung menggigitnya.
Ami mengerjapkan mata, lalu mengerutkan kening seolah sedang berpikir keras. Dia menoleh ke Wira, mengangkat es krimnya sedikit. “Wi... Wi...”
Wira menoleh, hatinya mencair seketika. “Eh, buat aku?” tanyanya, pura-pura terkejut.
Ami mengangguk kecil, lalu tertawa sendiri sebelum kembali sibuk menjilati es krimnya.
Ganes tersenyum, menatap Wira. “Sepertinya dia suka sama kamu.”
“Aku juga suka Ami,” balas Wira, menatap gadis kecil itu dengan penuh sayang.
Ami tiba-tiba menepuk tangan kecilnya ke paha Wira, lalu bergumam, “Wiwi!” sambil tertawa.
Wira mengangkat alis. “Wiwi?”
Ganes menahan tawa. “Sepertinya itu nama barumu.”
Wira berpura-pura berpikir keras. “Wiwi... Hmm, lucu juga.”
Ami mengangguk cepat, seolah setuju dengan dirinya sendiri. Wira tertawa, merasa bahwa sore ini adalah salah satu momen paling berharga dalam hidupnya.
POV Ami:
Ami suka es krim. Rasanya manis dan dingin di mulut. Mamah bilang harus pelan-pelan, tapi Ami tidak sabar. Begitu mamah membuka bungkusnya, Ami langsung menggigit, dan—brrr! Dingin sekali!
Ami mengerjap, lalu melihat ke samping. Ada pria di sana. Mamah tadi bilang namanya Om Wira, tapi Ami belum bisa mengucapkannya.
Ami menatap es krimnya. Lalu menatap pria itu lagi.
"Wi... Wi..." katanya sambil mengangkat es krim sedikit.
Pria itu terkejut. "Eh, buat aku?"
Ami tidak benar-benar tahu apakah ia ingin memberi atau hanya ingin berbagi kebahagiaan. Tapi ia mengangguk kecil, lalu tertawa sendiri.
Mamah tersenyum. "Sepertinya dia suka sama kamu."
Ami tidak mengerti sepenuhnya, tapi pria itu tersenyum lebar. "Aku juga suka Ami."
Ami senang. Ia menyukai suara pria itu. Tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan.
Jadi, Ami menepuk pahanya, seperti yang sering ia lakukan pada mamah jika ingin bermanja-manja. "Wiwi!" serunya, mencoba menyebut nama pria itu.
Pria itu mengangkat alis. "Wiwi?"
Mamah tertawa kecil. "Sepertinya itu nama barumu."
Pria itu berpura-pura berpikir, lalu mengangguk. "Wiwi... Hmm, lucu juga."
Ami mengangguk cepat. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia suka panggilan itu.
Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa Om Wiwi bukanlah orang asing lagi.
POV Wira:
Setelah Ami selesai makan es krim, Ganes akhirnya menurunkan Ami, membiarkannya berdiri sendiri di atas rerumputan.
Ami langsung berjalan dengan langkah kecilnya, menuju bunga-bunga liar yang tumbuh di sekitar taman. Dia berhenti di depan satu bunga kuning dan menatapnya lama.
“Dia suka bunga?” tanya Wira, mengamati Ami dengan takjub.
“Dia suka semua hal kecil yang menarik perhatiannya,” kata Ganes sambil duduk di bangku taman. “Kadang aku sampai kewalahan menjawab pertanyaannya.”
Wira ikut duduk, memperhatikan Ami yang kini sibuk mencabut bunga kecil itu. Dia berjalan kembali ke mereka dengan langkah goyah, lalu tanpa ragu menyerahkan bunga itu pada Wira.
“Wiwi,” katanya sambil mendorong bunga itu ke tangan Wira.
Wira merasa dadanya menghangat. “Untuk aku?”
Ami mengangguk kecil.
Ganes terkikik. “Sepertinya kamu dapat kehormatan besar hari ini.”
Wira tersenyum, menerima bunga itu dengan hati-hati. “Terima kasih, Ami.”
Sebagai balasan, Ami hanya tersenyum lebar, sebelum kembali berjalan ke rerumputan untuk mencari sesuatu yang baru.
Ganes menatap Wira. “Aku nggak nyangka dia bakal secepat ini akrab sama kamu.”
“Aku juga,” gumam Wira, masih melihat bunga kecil di tangannya.
Ternyata, Wira bukan saja jatuh hati pada Ganes, tapi dia juga jatuh hati pada si kecil Ami.

0 notes
Text
VI. Hati yang Kembali ke Rumah

Akhir pekan biasanya Wira habiskan dengan beristirahat di apartemen atau berolahraga. Namun, weekend kali ini berbeda—lebih spesial. Ia memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya.
Rumah itu selalu terasa nyaman, sehangat pelukan. Aroma teh manis dan masakan rumahan menyambutnya begitu ia melangkah masuk. Di dinding, pigura-pigura foto berjejer rapi, menceritakan kisah keluarga mereka dalam bingkai-bingkai kenangan.
"Ibu, Wira pulang," serunya sambil melepas sepatu.
Dari dalam, ibunya muncul dengan senyum lembut yang selalu menenangkan. "Anakku pulang," katanya, lalu menarik Wira ke dalam pelukan hangat.
"Selamat ulang tahun, Ibu yang paling hebat," ujar Wira seraya mengeluarkan sebuah tas kecil dari balik punggungnya.
Ibunya terkekeh pelan. "Ah, anak Ibu ini. Datangnya saja sudah hadiah."
Wira hanya tersenyum. Di dalam tas itu ada kado kecil—sebotol parfum yang sudah dibungkus cantik. Bukan Wira yang memilihnya, tapi seseorang yang akhir-akhir ini memenuhi pikirannya.
"Ganes yang bantu pilihkan kemarin," ucap Wira sambil menyerahkan hadiah itu.
Ibunya menerima kado itu dengan mata berbinar. "Terima kasih, Nak. Wah, Ganes? Temanmu?" tanyanya dengan nada penasaran.
Wira hanya tersenyum kecil, belum ingin menjawab.
Setelah itu, mereka makan berdua di meja makan yang penuh dengan hidangan kesukaan Wira. Masakan ibu memang selalu istimewa. Setiap suapan mengingatkan Wira pada masa kecilnya, pada hari-hari ketika hanya ada mereka berdua di dunia ini.
"Bagaimana pekerjaanmu?" Ibu bertanya, seperti biasa.
"Baik, Bu. Tidak ada masalah," jawab Wira.
Dan seperti yang sudah ia duga, setelah pertanyaan tentang pekerjaan, tibalah pertanyaan yang lebih sulit dihindari.
"Lalu... bagaimana dengan jodoh?"
Wira tersenyum kecil. Kali ini, ia tidak ingin menghindar. Memang ada sesuatu yang ingin ia ceritakan hari ini.
Ia menaruh sendoknya, menghela napas, lalu berkata, "Ada seseorang yang aku suka sekarang, Bu."
Ibunya langsung berbinar. "Benarkah? Siapa? Ceritakan dong."
Wira mengusap tengkuknya. "Namanya Ganes. Dia baik, mandiri, dan... dia seorang ibu."
Ibunya mengerjapkan mata, lalu tersenyum lebih lembut. "Ibu tunggal?"
Wira mengangguk pelan. "Iya. Dia punya anak, masih kecil."
Keheningan sejenak. Lalu, ibunya mengulurkan tangan, menggenggam tangan Wira dengan hangat. "Apa ini masalah buatmu, Nak?"
Wira menatap meja, berpikir sejenak sebelum menjawab. "Aku... tidak tahu. Aku tidak keberatan, Bu. Aku hanya takut. Bagaimana kalau anaknya tidak bisa menerimaku nanti? Bagaimana kalau aku tidak bisa menjadi bagian dari hidup mereka?"
Ibunya tersenyum, tatapannya penuh pemahaman. "Wira, kamu ingat nggak? Ibu juga dulu seorang ibu tunggal. Saat membesarkan kamu sendirian, ibu juga punya ketakutan yang sama."
Wira terdiam. Tentu saja ia ingat. Betapa ibunya dulu harus bekerja keras untuk membesarkannya sendirian, betapa ia sering merasa bersalah karena melihat ibunya kelelahan setiap malam.
"Tapi Ibu selalu percaya, kalau ada seseorang yang tulus, dia pasti akan menemukan jalannya sendiri. Begitu juga kamu, Nak."
Wira mengangkat wajahnya, menatap ibunya yang masih menggenggam tangannya.
"Kalau memang jodoh, pasti ada jalannya."
Hati Wira terasa lebih ringan. Kata-kata ibunya seperti embun di tengah pikirannya yang berkabut.
Mungkin, ini memang bukan tentang bisa atau tidak bisa. Tapi tentang mau atau tidak mau.

0 notes
Text
V. Langkah Pertama Wira

POV Ganes:
Sabtu sore, kafe mulai lengang saat jam kerja Ganes hampir selesai. Ia melepas apron dan meregangkan bahu, merasa lega akhirnya bisa beristirahat. Ketika menoleh ke arah pintu, matanya langsung menangkap sosok Wira yang duduk santai di sudut ruangan, menyesap kopinya dengan ekspresi tenang.
Ganes tidak bisa menahan senyum kecil. Wira sudah datang sejak satu jam yang lalu, duduk di tempat favoritnya sambil sesekali melirik ke arahnya. Seperti menunggu sesuatu. Atau… seseorang.
Saat Ganes berjalan ke arahnya, Wira segera bangkit dari duduknya.
"Udah selesai, Nes?" tanyanya, memasukkan ponselnya ke dalam saku.
Ganes mengangguk. "Akhirnya. Nunggu lama?"
"Nggak kok," Wira tersenyum kecil. "Aku memang mau ngajak kamu jalan sebentar."
Ganes mengangkat alis, sedikit terkejut. "Jalan? Ke mana?"
"Aku mau beli hadiah buat Ibu. Besok ulang tahunnya, dan aku butuh pendapat seseorang yang lebih paham soal hadiah buat perempuan."
Alasan yang masuk akal. Tapi ada sesuatu dalam cara Wira berbicara yang membuat Ganes merasa… ini bukan hanya soal hadiah. Ada ketulusan di matanya yang membuat Ganes tidak tega menolak.
"Oke," jawabnya akhirnya. "Tapi aku nggak jamin pilihanku bakal cocok buat ibumu, ya."
"Aku percaya seleramu," balas Wira cepat, membuat Ganes tertawa pelan.
Mereka berjalan berdampingan menuju pusat perbelanjaan. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah di udara. Wira membuka pintu mobil untuknya, membuat Ganes sedikit canggung. Sudah lama sekali sejak ada seseorang yang melakukan hal-hal kecil seperti ini untuknya.
Selama di perjalanan, obrolan mereka mengalir begitu saja—mulai dari hobi Ibu Wira, cerita tentang masa kecilnya, hingga bagaimana Ganes dulu sering membantu Gendis memilih hadiah untuk ibu mereka. Tidak ada kecanggungan. Tidak ada beban. Hanya percakapan ringan yang terasa nyaman.
Sesampainya di toko, Ganes dengan antusias membantu Wira memilih hadiah. Mereka tertawa saat Wira mencoba menebak-nebak parfum mana yang cocok untuk ibunya, dan akhirnya Ganeslah yang mengambil keputusan.
"Yang ini aja," katanya sambil menyerahkan sebuah botol parfum dengan aroma lembut. "Nggak terlalu kuat, tapi tetap elegan."
Wira menerima botol itu dan mengangguk puas. "Oke. Aku percaya kamu."
Setelah belanja, mereka berjalan-jalan sebentar, menikmati suasana kota yang mulai diselimuti cahaya senja. Ganes tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang muncul di dadanya.
Sudah lama sekali sejak ia merasa seperti ini—ringan, bebas, dan… bahagia.
Dan saat Wira menoleh padanya, tersenyum dengan tatapan yang lembut, Ganes tahu satu hal.
Pria ini sedang mencoba mengetuk pintu hatinya.
Dan yang lebih mengejutkan bagi Ganes adalah…
Ia mulai ingin membukanya.

0 notes
Text
IV. Renungan dalam Bus

POV Ganes:
Ganes menatap bayangannya di kaca jendela bus yang melaju pelan di tengah kemacetan sore. Hujan gerimis membentuk pola-pola kecil di permukaannya, seolah mencerminkan pikirannya yang kusut.
Pikirannya melayang pada seseorang.
Wira.
Pria itu datang begitu saja dalam hidupnya, seperti angin sejuk di tengah hari yang panas. Tanpa sadar, Ganes mulai terbiasa dengan kehadirannya. Awalnya hanya seorang pelanggan yang mampir setiap pagi, kemudian berubah menjadi seseorang yang membuatnya menunggu dengan diam-diam.
Ia tahu itu berbahaya.
Tapi ia juga tahu, perasaannya tak bisa sepenuhnya dikendalikan.
Sejak kapan Wira mulai terasa lebih dari sekadar pelanggan? Sejak kapan senyuman pria itu menjadi sesuatu yang ia nantikan? Sejak kapan perhatian kecil yang diberikan Wira membuatnya merasa… diperhatikan?
Mungkin sejak hari itu.
Hari di mana Wira menghentikan mobilnya di tengah hujan, menawarinya tumpangan tanpa ragu. Hari di mana Wira memberikan tisu agar tangannya tak terlalu basah. Hari di mana pria itu, dengan suara yang tak dibuat-buat, menanyakan tentang suaminya—dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ganes merasa nyaman mengucapkan, "Suamiku sudah nggak ada."
Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya.
Ganes menggigit bibirnya pelan.
Wira pria yang baik. Ia tahu itu.
Tapi apakah seorang pria baik akan menerima wanita seperti dirinya?
Seorang wanita yang tidak lagi sendiri, tapi juga tidak benar-benar lengkap.
Ganes punya banyak kekurangan. Hidupnya tidak sempurna. Ia adalah seorang ibu tunggal dengan masa lalu yang tidak bisa dihapus. Ia memiliki seorang anak yang lebih dulu harus menjadi prioritasnya.
Ia tidak lagi seperti gadis-gadis lain yang bisa memulai cinta dengan ringan, dengan lembaran baru yang bersih. Ia membawa cerita, luka, tanggung jawab—hal-hal yang mungkin akan menjadi beban bagi seseorang yang ingin masuk ke dalam hidupnya.
Dan Ganes tidak ingin Wira terbebani.
Ia tidak ingin pria itu merasa harus mengubah hidupnya demi seseorang yang belum tentu pantas.
Tapi di sisi lain…
Kenapa saat Wira tersenyum padanya, dunia terasa sedikit lebih hangat?
Kenapa saat pria itu menyebut nama "Ami" dengan lembut, hatinya terasa sedikit lebih ringan?
Kenapa, setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu yang sempat ia kira telah mati—harapan?
Bus berhenti di dekat rumah kakaknya. Ganes menghela napas panjang sebelum bangkit. Ia tahu, tidak ada jawaban yang bisa ia temukan hari ini.
Yang ia tahu, Wira telah mengetuk pintu hatinya.
Namun, apakah ia berani membukanya?
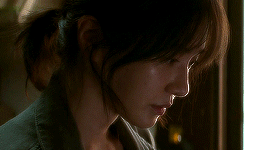
1 note
·
View note
Text
III. Hujan dan Sebuah Percakapan

POV Wira:
Wira merapikan mejanya sekilas, bersiap untuk pulang. Ia melirik jam tangannya—sudah lewat pukul sembilan. Di ruangan ini, hanya dia yang tersisa. Semua rekan kerjanya sudah lebih dulu meninggalkan kantor.
Dengan sedikit peregangan, Wira mengambil tasnya lalu turun ke parkiran. Begitu keluar gedung, angin dingin dan suara hujan lebat langsung menyambutnya. Ia menarik napas dalam sebelum bergegas menuju mobil. Saat melewati pos keamanan, ia menyapa satpam yang bertugas.
"Baru pulang, Mas Wira?"tanya Pak Satpam, bersandar di dekat pintu sambil menyeruput kopi dari termos kecilnya.
"Iya, Pak. Balik dulu."
"Hati-hati, Mas."
Wira mengangguk, lalu masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Ia memundurkan kendaraan perlahan sebelum akhirnya keluar dari kompleks kantor. Hujan masih deras, menari di kaca mobilnya dengan ritme yang tidak beraturan.
Saat melewati sebuah halte bus, pandangannya tertuju pada seseorang yang berdiri sendirian, menggigil di bawah derasnya hujan. Roknya tertiup angin, tasnya basah, dan rambutnya menempel di wajah.
Ganes.
Wira mengerem mendadak, hatinya berdebar. Sejenak ia terpaku, bergumul dengan pikirannya sendiri.
Dia istri orang... Aku tidak seharusnya terlalu berhubungan dengan istri orang.
Namun, melihat Ganes yang basah kuyup, berdiri sendirian di malam seperti ini, Wira tidak bisa tinggal diam. Ia menepi, lalu menurunkan kaca jendela.
"Ganes! Ganes!" panggilnya.
Ganes menoleh, tampak bingung sejenak, lalu mengangguk pelan.
"Bareng aja yuk! Macet, busnya lama!" ujar Wira, sedikit mengeraskan suaranya agar bisa terdengar di tengah hujan.
Ganes terlihat ragu, namun tubuhnya yang sudah menggigil memaksa dirinya untuk masuk.
"Mas Wira, makasih banyak ya. Maaf jadi ngerepotin."
"Nggak apa-apa, ini deres banget hujannya. Bisa-bisa di depan banjir."
Wira mengambil satu kotak tisu dari dashboard dan menyerahkannya ke Ganes. "Ini, pakai aja buat keringin tangan sama tasmu."
Ganes menerima tisu itu dengan senyum tipis.
"Ganes pulangnya ke mana?"
"Ke Halte Dukuh Atas aja, Mas."
"Udah sekalian aja sampai rumah, nanggung ini."
Wira mengecilkan AC mobilnya agar Ganes tidak semakin kedinginan. Suasana dalam mobil terasa lebih tenang dibandingkan hujan deras di luar.
Jalanan macet. Lampu-lampu mobil di sekitar mereka berpendar, memantul di permukaan jalan yang basah.
"Kok tumben shift malam?" tanya Wira untuk memecah keheningan.
"Iya, temanku ada acara malam ini, jadi dia minta tukar shift."
Wira mengangguk paham. "Lain kali kalau hujan begini, minta jemput suamimu aja, Nes."
Ganes terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Suamiku udah nggak ada, Mas."
Wira terpaku. Untuk beberapa detik, pikirannya benar-benar kosong. Ia mencoba merangkai kata yang tepat, namun tak satu pun terasa cukup.
"Maaf ya, Ganes... Aku nggak maksud mengungkit."
"Nggak apa-apa kok, Mas. Hehe." Ganes tertawa kecil, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang sulit diartikan.
Wira menarik napas dalam. Jantungnya masih berdetak kencang.
Lega.
Dan perasaan itu membuatnya merasa seperti orang jahat. Apakah aku keterlaluan?
Ia menggeleng pelan, mengusir pikirannya sendiri.
"Jadi kamu tinggal berdua aja sama Ami?" tanyanya, suaranya sedikit lebih lembut.
"Iya. Tapi kalau aku kerja, Ami dijagain kakakku. Sekarang juga aku mau pulang ke rumah kakakku dulu."
"Oh... Ami sekarang umur berapa?"
"18 bulan. Lagi lucu-lucunya!" jawab Ganes, senyumnya lebih lepas kali ini.
Wira ikut tersenyum. Obrolan mereka terus mengalir sepanjang perjalanan, membuat kemacetan tak terasa terlalu buruk. Hingga akhirnya, mobil Wira berhenti di depan rumah kakak Ganes.
"Udah sampai. Hati-hati, Nes."
Ganes mengangguk. "Sekali lagi makasih, Mas."
Wira menunggu sampai Ganes benar-benar masuk ke dalam rumah sebelum akhirnya melajukan mobilnya kembali. Malam itu, perjalanan pulangnya terasa lebih ringan. Ia bersenandung pelan, senyum yang sama sekali tak bisa ia tahan masih menghiasi wajahnya.
Hatinya berbunga-bunga.


2 notes
·
View notes
Text
II. Tertampar Kenyataan

POV Wira:
Pagi itu, Wira datang ke kafe dengan perasaan lebih ringan dari biasanya.
Ia baru saja kembali dari Bandung setelah menghadiri konferensi, dan kini, di dalam tasnya, ada sekotak kue bolen yang ia beli sebagai oleh-oleh. Untuk Ganes.
Bukan sesuatu yang berlebihan. Wajar saja, kan? Membelikan oleh-oleh untuk seseorang yang setiap hari ia temui, seseorang yang selalu menyapanya dengan ramah dan mengingat pesanannya tanpa perlu ia sebutkan.
Seseorang yang diam-diam membuatnya ingin datang ke kafe ini setiap hari.
Hari ini pun tidak berbeda. Begitu memasuki kafe, matanya langsung mencari sosok Ganes di balik meja bar. Dan seperti biasa, wanita itu ada di sana, tersenyum cerah ketika melihatnya datang.
“Pagi, Mas Wira! Kopinya seperti biasa?”
Wira mengangguk, lalu menaruh tasnya di meja. “Iya, seperti biasa.”
Sejenak, ia merasa ragu. Haruskah ia memberikannya sekarang? Apa ini terlalu aneh? Tapi Ganes sudah berjalan ke arah mesin kopi, dan jika ia tidak melakukannya sekarang, ia mungkin akan kehilangan keberanian.
Jadi, dengan sedikit batuk kecil untuk menenangkan diri, Wira merogoh tasnya dan mengeluarkan kotak kue bolen itu.
"Ini kemarin aku habis dari Bandung..." katanya, suaranya sedikit lebih pelan dari biasanya.
Ganes menoleh, lalu matanya membesar sedikit saat melihat kotak itu. "Wah, untuk aku, Mas?"
Wira mengangguk cepat. "Iya. Nggak banyak, sih. Cuma bolen aja."
Senyum Ganes semakin lebar. "Wah, terima kasih banyak! Ami pasti suka banget."
Ami?
Wira mengerjap. Ia merasa ada yang tidak beres dengan kalimat itu, tapi otaknya belum cukup cepat untuk memprosesnya.
Sampai akhirnya Ganes menambahkan dengan nada riang, “Ami anakkuuu~”
D E G.
Dunia di sekelilingnya seakan berhenti.
Untuk beberapa detik, ia hanya bisa menatap Ganes, seakan kata-kata itu belum sepenuhnya masuk ke dalam otaknya.
Ami.
Anakku.
Jantungnya berdegup kencang, tapi bukan dengan cara yang biasanya terjadi setiap kali ia berbicara dengan Ganes. Kali ini, ada sesuatu yang lain—sesuatu yang menusuk, menghantam, meremas dadanya begitu erat hingga rasanya sulit bernapas.
Ganes punya anak.
Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan, tapi ia memaksakan diri untuk tersenyum. "Hehehe… semoga suka ya, Ganes dan Ami."
Ganes tertawa kecil. "Pasti suka, Mas! Ami itu doyan banget sama yang manis-manis. Makasih banyak, ya!"
Wira mengangguk kaku, lalu segera membawa kopinya ke sudut ruangan.
Begitu ia duduk, ia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya.
Apakah wajar jika seorang pria dewasa tiba-tiba ingin menangis sendirian di kafe?
Ia menatap cangkir kopinya tanpa benar-benar melihatnya. Pikirannya masih berputar, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi.
Kenapa… selama ini ia tidak tahu?
Kenapa ia tidak pernah bertanya?
Kenapa ia begitu bodoh, begitu naif, hingga tidak pernah berpikir untuk menanyakan apakah Ganes sudah punya pasangan atau anak?
Selama ini, ia terlalu sibuk menikmati kehadiran Ganes. Terlalu sibuk menyusun rencana kecil untuk bisa semakin dekat dengannya. Terlalu sibuk memikirkan caranya mencuri sedikit lebih banyak waktu bersamanya.
Tapi sekarang… apakah semua itu harus berhenti?
Atau…
Apakah mengagumi seseorang dari jauh masih sah-sah saja?
1 note
·
View note
Text
I. Pertemuan Pertama
POV Wira:
Wira melepaskan kacamata yang sejak siang terasa semakin menekan batang hidungnya. Hari ini begitu panjang. Terlalu banyak angka dan laporan yang harus diselesaikan sebelum ia bisa benar-benar meninggalkan kantor. Dia menghela napas, menekan tombol shutdown pada komputernya, lalu berdiri sambil sedikit meregangkan badan.
Pukul lima sore. Akhirnya.
Dia segera mengambil tasnya dan berjalan keluar kantor. Langit di luar mulai berubah jingga, pertanda hari akan berakhir. Udara sore terasa sedikit hangat, bercampur dengan hembusan angin yang membuat dasi dan kemejanya sedikit berkibar.
Biasanya, setelah pulang kerja, Wira langsung menuju parkiran dan pulang ke apartemennya. Namun hari ini, kepalanya terasa begitu berat. Dia butuh sesuatu yang bisa membuatnya rileks sebelum benar-benar pulang.
Matanya tertuju pada sebuah kafe di sudut kompleks perkantoran.
Tempat itu sebenarnya bukan tempat asing baginya. Dia pernah ke sana beberapa kali, biasanya hanya untuk membeli kopi saat lembur. Tapi hari ini, dia ingin duduk sebentar, menikmati minuman tanpa terburu-buru.
Dia melangkah masuk. Aroma kopi dan musik akustik yang lembut segera menyambutnya.
Antrian tidak terlalu panjang, hanya ada dua orang di depannya. Wira berdiri santai, mencoba melihat menu di atas kasir. Tapi saat gilirannya tiba, sesuatu membuat tubuhnya serasa berhenti bekerja.
Wanita di balik meja kasir.
Sejenak, dunia terasa seperti dihentikan dengan satu tombol pause.
Matanya tertuju pada wajah wanita itu—tidak bisa berpaling.
Kulitnya tampak halus, dengan bibir merah alami dan hidung yang begitu sempurna. Rambut hitam panjangnya diikat ke belakang, menyisakan beberapa helai yang jatuh di sisi wajahnya. Dia tersenyum sopan, menunggu Wira menyebutkan pesanannya.
Tapi Wira tidak bisa berpikir.
Ada suara yang menyuruhnya untuk bicara, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Otaknya mendadak kosong, seakan semua bahasa yang dia kuasai tiba-tiba menguap begitu saja.
“Kak, mau pesan apa?” suara wanita itu membuyarkan kebekuannya.
Oh, sial. Berapa lama dia diam seperti orang bodoh?
“E—eh, aku…” Wira mengerjap cepat, memaksa dirinya kembali sadar. Matanya melirik ke papan menu, lalu menyebut sesuatu yang pertama kali ia lihat. “Ehm… Cappuccino.”
“Hot atau iced?”
“Hot,” jawabnya tanpa berpikir.
Wanita itu mencatat pesanan di layar kasir. “Baik, Kak. Cappuccino hot, ya. Mau pakai gula atau tanpa?”
“Eh… pakai.”
“Baik, totalnya tiga puluh ribu.”
Wira buru-buru merogoh dompetnya, menyerahkan uang tanpa menghitung ulang. Tangannya sedikit gemetar saat wanita itu memberikan kembalian dan struknya.
“Terima kasih. Silakan tunggu sebentar.”
Wanita itu tersenyum lagi. Sumpah, senyumnya bisa membuat orang lupa cara bernapas.
Wira mengambil napas dalam-dalam dan berjalan menuju area tempat duduk. Dia sengaja memilih meja yang menghadap langsung ke arah bar. Tidak ingin terlihat mencurigakan, dia membuka laptop dan mulai mengetik asal di dokumen kosong—seolah-olah dia benar-benar sibuk.
Tapi kenyataannya, dia hanya ingin melihat wanita itu lebih lama.
Dia mengamati cara wanita itu bekerja, menuangkan susu ke dalam cangkir, mencampurnya dengan espresso, lalu menambahkan latte art dengan ketelitian yang luar biasa. Setiap gerakan terlihat alami, seolah-olah dia sudah melakukan ini bertahun-tahun.
Di tengah keramaian kafe, Wira bertanya-tanya.
Apakah hanya dia yang menyadari kecantikan wanita itu? Kenapa semua orang di sini terlihat biasa saja? Mereka memesan kopi, berbicara dengan teman, menatap layar ponsel—tidak ada yang tampak terpesona seperti dirinya.
Wira menyandarkan punggungnya dan tersenyum kecil.
Mungkin ini pertama kalinya dalam hidupnya dia mengalami sesuatu yang sering terjadi di film-film romantis. Sebuah pertemuan sederhana yang terasa luar biasa.
Dan saat dia masih tenggelam dalam pikirannya, sesuatu terjadi.
Wanita itu menoleh ke arahnya.
Mata mereka bertemu.
Wira nyaris tersedak kopinya sendiri.
Tapi yang lebih mengejutkan lagi—wanita itu tersenyum kecil.
Senyuman yang samar, hanya sesaat, sebelum dia kembali fokus pada pekerjaannya.
Apakah itu hanya kebetulan? Atau… apakah dia juga menyadari kehadiran Wira?
Entahlah.
Yang pasti, Wira sudah membuat keputusan dalam hatinya.
Besok, dia akan kembali ke kafe ini. Dan lusa. Dan hari-hari berikutnya.
Karena sekarang, dia punya alasan baru untuk menikmati kopi.

POV Ganes:
Ganes mengikat kembali rambutnya yang mulai terlepas dari ikatan. Hari ini cukup sibuk, tapi dia sudah terbiasa dengan ritme kerja seperti ini. Aroma kopi yang menguar, suara mesin espresso yang berdengung, serta alunan musik akustik di latar belakang—semuanya sudah menjadi bagian dari dunianya.
Di sela-sela membuat kopi, pikirannya sempat melayang ke Amika. Sudah jam lima lebih, berarti sebentar lagi Gendis pasti memberi kabar kalau putrinya sudah makan sore. Ganes tersenyum kecil membayangkan Amika yang mulai lancar mengoceh dengan bahasa bayi yang hanya bisa dipahami olehnya.
Tiba-tiba, suara di depan meja kasir menariknya kembali ke realitas.
“Kak, mau pesan apa?” tanyanya, seperti biasa, dengan senyum sopan.
Pria di depannya tampak sedikit bingung. Matanya menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan—seperti seseorang yang baru saja tersadar dari lamunan panjang.
Ganes menunggu, sedikit mencondongkan tubuh untuk memastikan pria itu mendengar pertanyaannya.
“E—eh, aku…”
Ganes menahan senyum saat melihat pria itu gelagapan, lalu dengan cepat melihat ke papan menu. Dia sering melihat pelanggan bingung memesan, tapi yang satu ini reaksinya agak berlebihan.
“Ehm… Cappuccino.”
“Hot atau iced?”
“Hot,” jawab pria itu buru-buru.
Sambil mencatat pesanan, Ganes bertanya lagi, “Mau pakai gula atau tanpa?”
Pria itu tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, “Eh… pakai.”
Setelah menyebutkan total harga, pria itu menyerahkan uang dengan gerakan yang agak kaku. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil kembalian. Ganes berusaha menahan senyum.
Setelah pria itu pergi ke meja, Ganes mulai menyiapkan pesanannya. Dengan gerakan terlatih, dia menuangkan espresso ke dalam cangkir, lalu mengukir latte art sederhana di atasnya. Selama bertahun-tahun menjadi barista, dia sudah terbiasa dengan pelanggan yang sering kembali, entah karena kopi atau sekadar suasana kafe.
Namun, entah kenapa, dia bisa merasakan tatapan pria itu dari kejauhan.
Saat meletakkan cappuccino di meja pickup, dia tanpa sengaja menoleh ke arahnya.
Mata mereka bertemu.
Ganes sempat terkejut, tapi kemudian memutuskan untuk tersenyum kecil. Hanya sesaat, sebelum kembali fokus pada pekerjaannya.
Pria itu tampak kaku, seperti baru saja ketahuan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan.
Ganes hanya menghela napas pelan dan melanjutkan pekerjaannya.
Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar di saku apron. Saat istirahat nanti, dia akan membaca pesannya—kemungkinan dari Gendis yang memberitahu bahwa Amika baik-baik saja.
Sementara itu, di sudut ruangan, pria tadi masih duduk dengan laptop terbuka di depannya.
Ganes tersenyum dalam hati.
Mungkin besok dia akan datang lagi.

1 note
·
View note
Note
Hy siapa pacarmu?
Pacarku namanya Ganeswari alias ofGyuyoung yang paling cantik sedunia!

0 notes
Text
Wi Hajun (위하준), 1991.

Wi Ha-jun (born August 5, 1991) is a South Korean actor and model known for his versatility in both action and thriller genres. He made his acting debut in 2012 and gradually gained recognition through roles in films like 𝗚𝗼𝗻𝗷𝗶𝗮𝗺: 𝗛𝗮𝘂𝗻𝘁𝗲𝗱 𝗔𝘀𝘆𝗹𝘂𝗺 (2018) and 𝗠𝗶𝗱𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁 (2021).
His breakthrough came in 2021 with 𝗦𝗾𝘂𝗶𝗱 𝗚𝗮𝗺𝗲, where he played police officer Hwang Jun-ho, earning global fame. He then starred in the action-packed drama 𝗕𝗮𝗱 𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗿𝗮𝘇𝘆 (2021), followed by a compelling role in 𝗟𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 (2022). In 2023, he impressed audiences with his portrayal of a ruthless gangster in 𝗧𝗵𝗲 𝗪𝗼𝗿𝘀𝘁 𝗼𝗳 𝗘𝘃𝗶𝗹.
With his strong screen presence and action skills, Wi Ha-jun continues to rise as one of Korea’s most sought-after actors.
3 notes
·
View notes